Terkait dengan kepentingan politik elektoral, bahasa menjadi salah satu determinan yang turut menentukan dukungan publik terhadap seorang politisi. Dalam hal ini, bahasa dibangun dan digunakan untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik dimana pada akhirnya, bahasa turut menentukan elektabilitas partai politik dan calon anggota legislatifnya. Mengapa demikian? kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dengan adanya fungsi ganda dari bahasa. Secara pragmatis, bahasa hanya memiliki fungsi komunikatif dimana dalam hal tersebut bahasa diibaratkan sebagai kurir yang membawa berbagai muatan makna untuk diantar ke tujuan akhirnya, yaitu publik. Namun, sebagai penanda identitas, bahasa telah melampaui fungsi harfiahnya dimana sebagai identitas, bahasa bukan sekedar sebagai kurir yang mengantar pesan, melainkan pesan itu sendiri.
Adanya fungsi ganda dari bahasa dengen demikian telah mendorong para pemburu kekuasaan berupaya untuk memberdayakan bahasa dalam ikhtiar politiknya. Bahasa dalam perkembangannya kemudian dipelajari secara khusus demi kepentingan kekuasaan dan dari proses tersebut lahirlah suatu varian baru yang kini kita kenal sebagai bahasa politik. Ditelaah lebih jauh, bahasa politik dalam praksisnya ternyata berbeda dengan bahasa keseharian, berbeda dengan bahasa sastra, serta berbeda pula dengan bahasa akademik.
Bahasa keseharian merupakan bahasa pada level makna pertama. Pada bahasa jenis ini tidak akan ditemukan adanya jarak semantik antara apa yang dituturkan dengan apa yang dimaksudkan. Kalau pun toh ditemukan distorsi makna, hal tersebut dilakukan terbatas pada kepentingan etika yang dilakukan melalui proses ameliorasi, eufimisme, serta kiasan dan majas lainnya. Di dalam jagat sastra, bahasa yang digunakan seringkali merupakan bahasa pada tingkat makna kedua yang bersifat interpretatif (harus dipahami dan diinterpretasikan lebih lanjut). Pada ranah sastra, makna tidak dicari dengan cara mencocokkan bentuk tuturan dengan makna leksikal yang melekat padanya, makna pada karya sastra justru diperoleh melalui penghayatan subyektif terhadap simbol, rasa dan intertekstualitas. Sementara itu, bahasa akademis dilahirkan untuk memenuhi dahaga kejujuran, kebenaran dimana kejelasan dan ketuntasan dari setiap masalah yang dibahas pada ranah akademik menjadi tujuan akhir yang diidamkannya.
Bagaimana dengan bahasa politik? Bahasa jenis ini memliki ciri otentik tersendiri karena lahir dari rahim yang berbeda dimana bahasa politik lahir dari masyarakat terpelajar yang sedang berupaya merengkuh kekuasaan. Tujuan bahasa politik dalam hal ini tidak hanya menyampaikan pesan, melainkan menggerakkan publik untuk mengambil keputusan. Keberhasilan bahasa politik juga tidak bisa ditakar begitu saja ketika ujarannya selesai dituturkan, tetapi harus diendapkan karena bersifat akumulatif melalui proses refleksi yang cukup panjang. Bahasa politik merupakan bahasa lapis ketiga, keempat dan bahkan (tak terhingga). Dalam bahasa politik, pencarian makna tidak bisa diperoleh hanya melalui penelusuran simbol. Dalam bahasa politik, intertekstualitas dan kontekstualitas bisa turut mengubah makna sebuah ungkapan hingga sama sekali berbeda dengan wujud leksikalnya.
Bagaimana memahami bahasa politik? Untuk memahami bahasa dalam konteks tersebut, Dell Hymes (1974) membangun rumus speaking untuk membantu bagaimana memahami bahasa politik. Menurut Hymes, upaya mengungkap makna tuturan pada bahasa politik bisa diimbangi dengan upaya mengungkap speaking, yaitu Setting (latar belakang fisik dan batin yang dibicarakan politisi ketika berbicara), Participants (aktor, siapa tokoh politik dan pendengarnya), Ends (tujuan dari pembicaraan yang diangkat politisi), Act Sequence (urutan atau cara yang dilakukan politisi ketika berbicara), Key (nada dan semangat pembicaraan yang dilakukan politisi), Intstrumentalities (instrumen, saluran atau media yang digunakan oleh politisi ketika berbicara), Norms (norma sosial yang dijunjung politisi dan pendengar ketika berbicara wacana politik), dan Genre (jenis pembicaraan yang dibahas oleh politisi)
Pada konteks politik di Indonesia saat ini, rumusan Hymes diatas bisa dimanfaatkan oleh masyarakat calon pemilih untuk memverifikasi berbagai informasi politik yang diterimanya. Upaya ini penting dilakukan agar pemilih dapat menghindari adanya jebakan bahasa (language trap) yang ada disekitarnya. Lebih dari itu, melalui rumusan Hymes di atas, masyarakat juga bisa melakukan penilaian bagaimana kualitas dan integritas dari politisi yang akan didukungnya. Singkatnya, melalui bahasa, rumus Hymes bisa digunakan untuk mengidentifikasi lebih jauh bagaimana strategi bahasa politik yang akan digunakan oleh para politisi ketika menyuarakan berbagai gagasan pemikirannya.
Bahasa politik selayaknya tidak selalu berlumur dengan kebohongan. Terdapat banyak informasi yang faktual dan bisa dipercaya hadir dalam berbagai wacana politiknya. Akan tetapi, perlu diwaspadai, baik itu kejujuran maupun kebohongan, dalam bahasa politik, selalu berorientasi pada kekuasaan. Oleh sebab itu, upaya verifikasi bahasa politik sebenarnya tidak boleh berhenti pada dikotomi pemilahan jujur-bohong atau faktual-fiktif, melainkan pada ada motif apa saja yang secara implisit hendak disampaikan oleh politisi. Bahasa politik bisa eksis di ruang publik dalam berbagai bentuk mulai dari penjelasan informasi, propaganda, intimidasi, bahkan ilusi. Sebagai penjelasan misalnya, bahasa politik bisa digunakan untuk merekonstruksi realitas melalui simbol bunyi, aksara dan rupa tertentu kepada publik. Bahkan, tak jarang pula data statistik, kalkulasi dan estimasi politik sering direkonstruksi dan dihadirkan sebagai penjelasan politis. yang diperhalus dengan teknologi mutakhir dari instrumen penyebar informasi seperti televisi, internet dan instrumen lain yang sejenis.
Lalu bagaimana “bentuk-bentuk khusus” bahasa politik? Berikut beberapa contoh bentuk dan penggunaannya di Indonesia.
Bahasa Metafora
Secara leksikal, metafora merupakan penggunaan kata atau kelompok kata bukan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan atau kiasan berdasarkan kesamaan atau perbandingan. Metafora dapat diciptakan berdasarkan adanya kesamaan dua hal atau peristiwa berbeda yang memiliki aspek-aspek yang sama. Terdapat dua istilah penting dalam sebuah metafora yaitu istilah primer dan istilah sekunder. Istilah primer adalah hal-hal yang dilukiskan dalam sebuah metafora, sedangkan istilah sekunder adalah deskripsi mengenai hal-hal yang dilukiskan dalam sebuah metafora.
Secara etimologis, metafora berasal dari bahasa Yunani, metaphora yang berarti “memindahkan”, yaitu dari meta yang berarti “di atas”, dan pherein yang berarti “membawa” Metafora merujuk kepada proses linguistik yang mana aspek tertentu dari suatu obyek dibawa atau dipindahkan kepada obyek lain; dengan demikian, obyek kedua diungkapkan seolah-oleh obyek tersebut adalah obyek yang pertama. Dengan memanfaatkan metafora, seseorang berkesempatan menjelaskan sesuatu tanpa harus menyampaikannya. Metafora memungkinkan sebuah pesan yang kompleks, abstrak dan rumit diterima sebagai pesan yang sederhana.
Para politisi sendiri memiliki tantangan besar untuk menyampaikan sesuatu yang abstrak dan rumit menjadi sesuatu yang mudah dipahami, misalnya mereka harus berbicara tentang ekonomi makro, demokrasi, tatanan sosial, mentalitas bangsa, bahkan terkadang mengenai spiritualisme. Thomas dan Wareing (1999) mengemukakan bahwa berbagai tema tersebut merupakan tema-tema besar nan rumit. Jika dijelaskan secara teknis, hanya ada sedikit anggota masyarakat yang akan paham. Padahal, para politisi justru berharap agar perkataan mereka didengarkan dan dipahami oleh khalayak sebanyak mungkin sekaligus dalam durasi pertemuan yang sesingkat mungkin.
Persoalan tersebut yang coba diatasi para politisi dengan menggunakan metafora. Melalui penggunaan metafora yang tepat guna, suatu gagasan lebih mudah tersampaikan. Metafora ternyata juga mampu turut membangkitkan emosi, kesan, dan perasaan tertentu karena dalam politik, emosi, kesan dan perasaan adalah modal yang cukup berharga, mengapa demikian? Karena, pilihan politik seseorang tidak terbatas selalu disadari hanya pada pertimbangan rasional atas visi dan misi dari kandidat semata. Cukup banyak pemilih menetapkan pilihannya berdasarkan perihal sentimental seperti perasaan suka atau tidak suka, kesamaan identitas, kesamaan latar belakang hingga pertimbangan jenis kelamin.
Pada pemilihan presiden tahun 2014 lalu, misalnya, calon presiden Prabowo Subianto memiliki sebutan khas untuk menggambarkan Indonesia yang ideal di waktu yang akan datang. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyuarakan harapannya agar kelak nanti Indonesia akan menjadi “Macan Asia”. Pernyataan tersebut terus-menerus direproduksi diberbagai kesempatan mulai dari orasi politik, teks iklan hingga video kampanye politiknya. Begitu intensnya direproduksi, slogan “Macan Asia” pun identik dengan nama Prabowo sendiri. Pertanyaannya, mengapa ia memilih macan sebagai simbol metaforanya? Tentu karena ada sisi bahasa politik yang menegasikan sosok Prabowo.
Prabowo Macan Asia sebuah metafora
Bisa jadi, macan digunakan Prabowo bukan berarti secara harfiah hendak menyajikan pertunjukan magis untuk mengubah penduduk Indonesia menjadi seekor binatang buas. Dengan menggunakan metafora macan, Prabowo secara implisit hendak mengemukakan bahwa Indonesia bisa tumbuh menjadi bangsa yang gagah, berwibawa dan ditakuti di Asia. Sebagaimana macan di habitatnya, Prabowo optimis bahwa ia mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang perkasa. Secara politik, “Macan” juga diartikan sebagai bangsa yang memiliki kedaulatan, ditakuti bangsa lain dan memiliki akar ideologi yang kuat. Bisa jadi, karena latar belakangnya sebagai militer pula, Prabowo memilih metafora macan yang juga mencakup berbagai aspek pertahanan. Misalnya, macan diartikan sebagai bangsa yang memiliki prajurit yang gagah dalam jumlah banyak, memiliki persenjataan yang canggih, dan selalu waspada terhadap setiap ancaman disekitarnya.
Sementara itu, kandidat presiden lainnya, yang terpilih sebagai persiden Republik Indonesia, Joko Widodo, juga seringkali menggunakan metafora untuk menyebarkan gagasan utamanya. Slogan metafora populer yang turut mendongkrak kerja politiknya ialah “Revolusi Mental” Sebagai instrumen kampanye, slogan Revolusi Mental ternyata bekerja amat efektif. Difusi dua kata tersebut mengandung gagasan dan visi jauh lebih besar meski terlihat sederhana. Metafora Revolusi Mental juga memperlihatkan kesan gagah dan berani.
Akan tetapi, pengguna bahasa Indonesia sendiri cenderung mengartikan revolusi sebagai terminologi yang terbatas pada konteks sosial dan politik. Padahal, kata revolusi memiliki beberapa definisi. Revolusi diartikan sebagai perubahan sosial yang cepat dan mendasar. Dalam ilmu eksakta, revolusi diartikan sebagai proses peredaran bumi dan planet lainnya untuk mengelilingi matahari. Akan tetapi, pengertian yang kedua ternyata tidak cukup populer untuk digunakan sebagai slogan politik. Dengan memanfaatkan konsep revolusi, Jokowi seakan membangun kesan bahwa ia akan melakukan perubahan fundamental dalam waktu singkat. Tanpa secara langsung harus mengatakan “mendasar” dan “cepat”, ia sendiri sudah membangun persepsi tersebut pada benak publik; dan publik terlihat mengafirmasi “pesan tersembunyi” tersebut tanpa menyadari bahwa mereka telah menyetujuinya.
Pertanyaannya, apakah revolusi mental merupakan suatu program politik yang visible atau bisa dirasakan secara langsung? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu ditelaah lebih jauh arti “revolusi” dan “mental”, baik secara semantik maupun pragmatik. Mengingat revolusi merupakan perubahan yang cepat dan mendasar, maka sebagai program politik, makna cepat yang tekandung dalam “Revolusi Mental” seharusnya dijabarkan dalam berbagai bentuk data. Berapa durasi yang dibutuhkan sehingga program Jokowi tersebut bisa dianggap cepat? Mengingat masa jabatan relatif presiden hanya selama lima tahun sehingga rincian tersebut penting untuk selayaknya dipaparkan dalam bentuk dokumen yang detail.
Bagaimana dengan penggunaan kata “mental” sendiri? Secara leksikal, mental berarti suatu “kemampuan yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia” yang bukan bersifat jasmani dan terlihat kasat mata. Berdasarkan pengertian tersebut, mental sesungguhnya tidak berwujud tunggal. Mental berhubungan dengan unsur lain seperti spiritualisme, motivasi, citra diri, kebahagiaan serta pandangan manusia terhadap dunianya. Hampir semua unsur tersebut ternyata bersifat sangat personal dan unik, eksis dalam dunia batin dan psikologis manusia. Dalam hal ini, bagaimana bisa Jokowi mendayagunakan kewenangan politisnya sebagai presiden untuk menyentuh berbagai hal yang justru bersifat personal tersebut?
Satu contoh misalnya, dalam visi dan misinya tentang pendidikan, Jokowi justru tidak menjelaskan bagaimana menggarap aspek mental manusia, dalam konteks ini khususnya mental para peserta didik. Program bidang pendidikan yang ia suarakan justru menyangkut aspek struktural dengan prioritas pada permasalahan struktur dan infrastruktur, yakni seputar penataan kembali kurikulum, evaluasi model penyeragaman, penataan pembobotan palajaran, peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan fasilitas transportasi menuju pendidikan, hingga penataan distribusi guru. Apakah berbagai persoalan mental manusia bisa tersentuh melalui berbagai program tersebut?
Apakah terpenuhinya berbagai aspek struktur dan infrastruktur bisa menjadi cerminan atau bisa dijadikan parameter tunggal bagi meningkatnya kualitas mental manusia? Apakah kondisi mental manusia bisa disamakan dengan logika kapital dimana peningkatan modal dan berbagai sarana pendukungnya bisa turut mendorong peningkatan produksi dan kualitas produknya secara bersamaan? Dalam logika kapital, suatu produk diposisikan sebagai obyek yang ditentukan oleh kepentingan pemilik kapital. Lalu, dimana posisi peserta didik dalam dunia pendidikan? Apakah sebagai obyek yang dijadikan target sasaran tembak “Revolusi Mental” atau sebagai subyek yang secara dialektis memengaruhi jalannya progam tersebut?
Pada temuan kasus lain, slogan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilu 2014, “Rumah Besar Umat Islam,” juga menggunakan metafora yang menarik meski terlihat sederhana. Kata rumah, yang berarti suatu bangunan tempat tinggal, bernaung, berlindung sekaligus tempat pulang, dimanfaatkan untuk merepresentasikan sebuah institusi politik. Bagi publik sendiri, rumah mungkin dianggap berkonotasi positif karena merupakan tempat yang dianggap nyaman dan senantiasa dirindukan. Di rumahlah setiap kelelahan dilepaskan, kerinduan diungkapkan dan setiap doa dilafazkan. Melalui metafora tersebut, pengurus partai berlambang Kabah ini seolah ingin memberikan seruan kepada umat Islam Indonesia untuk kembali ke “rumah” meski mereka telah bepergian ke berbagai institusi politik.
Mengapa demikian? Pesan untuk pulang ke rumah ternyata memiliki latar belakang historisnya sendiri. Sebab, sejak tahun 1977, partai tersebut memang menjadi satu-satuya rumah tempat menyalurkan aspirasi politik sebagian besar umat Islam Indonesia setelah adanya difusi partai. Berbagai partai Islam peserta pemilu 1955 seperti Parmusi, Perti, NU hingga PSII telah digabungkan hanya menjadi satu partai, yaitu PPP. Praktis, PPP menjadi satu-satunya institusi politik yang “legal” bagi umat Islam Indonesia hingga akhir tahun 1990-an. Ketika keran reformasi telah dibuka pada 1998, tidak sedikit tokoh-tokoh Islam Indonesia yang menyempal dari PPP. Mereka mendirikan partai politik sendiri. Misalnya, dengan dukungan sejumlah ulama di Jawa Timur, Nahdliyin mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan sebagian nahdliyin lain mendirikan Partai Nahdatul Ummah. Sementara itu, sebagian anggota Muhammadiyah mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Dan sederet hal yang terjadi dalam sikus bahasa politik.
Efek Pronomina
Dalam kajian tentang kelas kata, pronomina lazim diartikan sebagai kata ganti. Terdapat empat jenis pronomina, yakni pronomina orang (persona), pronomina milik atau kepemilikan, pronomina petunjuk, dan pronomina penghubung. Di antara tipologi pronomina tersebut, tipe pronomina persona, misalnya seperti saya, anda, kita, kami dan mereka, merupakan jenis yang paling kentara digunakan dalam bahasa politik. Pronomina sendiri bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan pemihakan atau keberpihakan yang menunjukkan kesatuan. Dengan menggunakan pronomina yang tepat, politisi berupaya mengidentifikasi posisi dirinya diantara setiap pendengarnya sehingga bisa membangkitkan rasa dekat dengan setiap loyalisnya.
Pada pemilu presiden 2019 lalu, dua kandidat presiden kala itu, Prabowo dan Jokowi, memberdayakan pronomina kita. Calon presiden nomor satu, Prabowo Subianto, menyuarakan ungkapan lama yang berbunyi “Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi; Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi”. Sementara itu calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo, menggunakan tagline dengan nada yang lebih berani, yaitu “Jokowi Adalah Kita”. Siklus produksi dari tagline kedua kandidat tersebut terus dilakukan dan banyak ditemukan dalam setiap pidato, baliho, spanduk hingga leaflet yang disebar kepada publik.
Pada momentum dan tempat yang berbeda, penggunaan kita juga hadir dalam setiap wacana politik. Pada pemilu presiden tahun 2004 misalnya, Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan kita melalui tagline “Bersama Kita Bisa” Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menggunakan kata kita pada tagline-nya, “Partai Kita Semua” untuk meraih dukungan kaum muda kala itu. Di Amerika Serikat, presiden Barack Obama menggunakan frasa “Yes We Can” dalam pemilihan presiden periode pertamanya. Ketika terpilih, Obama membungkus berbagai programnya dengan slogan “Change We Can Believe in”
Dibandingkan dengan pronomina persona lainnya, kata kita memiliki keunggulan tersendiri dalam kontestasi politik karena seolah menyatakan kesatuan antara penutur dengan setiap pendengarnya. Dengan kata kita, penutur secara performatif menyatakan bahwa dirinya berada di pihak yang sama dengan setiap mitra tuturnya. Pronomina kita juga seolah menghadirkan rasa egaliter karena menempatkan pendengar pada posisi yang sama dengan politisi sebagai penuturnya. Kata kita mampu menumbuhkan empati yang tinggi jika digunakan pada konteks yang tepat.
Pada suatu peristiwa, ketika dipecat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional (PAN), politisi Wanda Hamidah menggunakan strategi permainan pronomina dalam pernyataan politis yang ditayangkan salah satu stasiun televisi nasional kala itu. Wanda dipecat karena terang-terangan mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden tahun 2014, meskipun ia merupakan kader PAN, partai yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dalam konferensi persnya, ia menyatakan tidak merasa kecewa dipecat oleh PAN. Namun, ia justru khawatir dengan kekuatan politik yang memasung suaranya dan suara rakyat pada umumnya. Disitulah Wanda memainkan pronomina kata saya, anda, kita, dan rakyat secara bergiliran sebagai berikut
“Saya tidak kecewa dan saya tidak menyesal atas pemberhentian dari Partai Amanat Nasional. Tapi sebaliknya, kekecewaan saya justru terhadap apa yang mengancam kita. Yaitu hasrat kekuatan elit politik yang hendak memasung suara saya dan hasrat kekuatan elit yang hendak memasung suara rakyat” Dengan formulasi pernyataan tersebut, Wanda seolah mengaburkan makna kata saya, anda, kita dan rakyat dengan menggunakannya secara bergantian seolah-olah semua kata tersebut bersinonim. Dengan permainan tersebut, Wanda berupaya mengajak penonton agar berposisi sama seperti dirinya. Jika berhasil, strategi pengaburan yang dilakukan oleh Wanda akan membuat persoalan individu seolah-olah menjadi persoalan publik atau personal trouble menjadi public issue.
Pada wacana politik, permainan pronomina seringkali dimainkan secara bergantian dengan formulasi kalimat aktif dan kalimat pasif. Para politisi memiliki kecenderungan memanfaatkan kalimat aktif ketika menyuarakan kabar baik kepada publik. Sebaliknya, para politisi cenderung menggunakan kalimat pasif ketika menyampaikan kabar buruk. Pemilihan dua formulasi kalimat aktif dan pasif tersebut tentu saja memiliki konsekuensi sosial yang berbeda karena turut mengakibatkan timbul dan tenggelamnya eksistensi seorang agen sosial. Jalbert (1994) mengemukakan bahwa dalam kalimat pasif, subyek seringkali tidak hadir karena keberadaannya disembunyikan dari orang lain bahkan ditiadakan. Hal tersebut seolah-olah berarti bahwa ketika agen suatu peristiwa atau tindakan ditiadakan, maka seolah-olah memberi kesan bahwa peristiwa tersebut terjadi dengan sendirinya. Jika suatu peristiwa menimbulkan korban jiwa, maka formulasi kalimat pasif akan berimplikasi logis pada anggapan umum: jangan mencari siapa pelakunya.
Misalnya, Jalbert mengangkat contoh pemberitaan yang dilakukan oleh sejumlah stasiun televisi internasional ihwal konflik Timur Tengah. Misalnya, terdapat berita yang bertajuk: “Damour, nine miles south of Beirut, was under attack all day, and the port city of Sidon is under heavy siege” (Damour, wilayah yang terletak sekitar sembilan miles dari Beirut, telah diserang sepanjang hari. Sementara itu, kota Sidon juga telah dikepung). Bagi mereka yang melek informasi, jamak diketahui siapa yang menyerang Damour, yakni tentara Israel. Namun, dengan menggunakan formulasi kalimat pasif, seolah-olah menjadi tidak ada yang bertanggung jawab atas persitiwa penyerangan tersebut. Perhatian pemirsa digiring sedemikian rupa untuk berfokus pada peristiwa penyerangan dan segala akibatnya, bukan berfokus kepada siapa pelaku penyerangan tersebut.
Instrumen simplifikasi dan generalisasi
Ketika melangsungkan kampanye, sebagian besar politisi selalu menunjukkan ambisi yang sangat besar untuk menaklukkan publik. Strategi kampanye yang membangkitkan emosi, meluapkan kegembiraan, dan mengealu-elukan identitas komunitas seringkali dilancarkan. Ambisi tersebut seringkali mengakibatkan mereka alpa terhadap akurasi. Kejernihan-berpikir dinomorduakan dan relasi sebab-akibat gagal diuraikan. Akibatnya, tidak sedikit politisi yang terjebak pada orasi politis dengan pola pikir yang general (menyamaratakan kesimpulan) dan simplifikatif (terlalu menyederhanakan). Pada sebagian kasus, logical fallacy tersebut seringkali terjadi karena ketidakcakapan politisi sebagai penuturnya, namun pada beberapa kasus lain, kesalahan terjadi dengan niat untuk memanipulasi persepsi dan kesadaran publik.
Doyin, Mukh dan Wagiran (2012) mengemukakan bahwa logical fallacy lazim terjadi dikarenakan lima sebab, antara lain generalisasi yang terlalu luas, kerancuan analogi, kekeliruan kausalitas, kesalahan relevansi, dan penyandaran pada prestise seseorang (menyandarkan analisa pada pendapat seseorang yang sudah terkenal, misalnya akademisi). Akan tetapi, kecenderungan generalisasi dan simplifikasi dalam aktivitas politik seringkali terjadi karena adanya kepentingan politik. Simplifikasi dilakukan karena subyek sebagai penutur wacana politik enggan atau tidak memiliki kapabilitas untuk menguraikan suatu permasalahan secara detail dan sistematis, baik dalam hal kronologis ataupun kausalitas. Di lain, sang aktor politik tidak mau dianggap awam ketika membahas konten dari wacana politis yang sedang dilemparnya sehingga terjadilah generalisasi dan simplifikasi.
Pasa suatu temuan kasus, Pada acara Pengukuhan Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 untuk periode 2013-2018 di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (10/02/2014), ketua umum Golkar Aburizal Bakrie menanggapi maraknya peredaran gambar Soeharto dengan narasi tulisan “Piye Kabare, le? Enak Zamanku, to?” Menurut Ical (sapaan ARB), fenomena tersebut merupakan suatu bukti bahwa rakyat rindu Soeharto. Lantaran Soeharto adalah Golkar, Ical secara sepihak dan simplifikatif menekuk kesimpulan bahwa rakyat ingin Golkar kembali memimpin.
“Ada keinginan rakyat untuk kembali ke Golkar dan diakui oleh pengurus daerah tentang kerinduan kembali ke Golkar, dan kerinduan kepada Pak Harto juga terlihat di wajah mereka,” kata Ical. Untuk itu, Ical meminta kepada seluruh organisasi massa yang tergabung dalam Golkar untuk menangkap aspirasi masyarakat tersebut. “Jangan malu-malu mengakui bangga kepada Orde Baru. Jika malu-malu harapan yang disampaikan rakyat bisa-bisa ditangkap partai lain, jangan ragu-ragu Golkar yes Orde Baru yes,” ungkapnya. (Tribunnews, 10 Februari 2014).
Cara Ical mengambil simpulan tersebut merupakan pola pikir yang simplifikatif bahkan cenderung bengkok. Ia berupaya mengarahkan publik untuk mengambil simpulan yang sama dengannya. Padahal maraknya kehadiran sticker Soeharto dengan tulisan “Enak Zamanku, to?” tidak bisa hanya dimaknai secara leksikal sebagai ekspresi kerinduan publik terhadap Soeharto. Teks tersebut muncul pada situasi ketika rakyat mengalami ketidakpuasan dengan pemerintah kala itu dimana sticker tersebut merupakan bentuk ironi untuk Soeharto yang kinerjanya dianggap buruk tidak sesuai dengan harapan rakyat.
Pada kesempatan yang berbeda, Ical ketika berkampanye juga mengajak publik untuk turut memenangkan Golkar. Namun, Ical tidak memberikan argumen rasional mengenai manfaat yang diperoleh publik apabila Golkar menang. Ical justru membuat simpulan yang didasarkan pada sentimen perihal kerinduan terhadap Orde Baru. “Kenapa kita harus menangkan Golkar? Karena hanya Golkar yang pernah memimpin negeri ini selama 32 tahun,” katanya sebagaimana dikutip Tirbunnews (19 Maret 2014).
Pada pemilu 2014, Partai Golkar memiliki slogan yang berbunyi “Suara Golkar Suara Rakyat” Akan tetapi, slogan tersebut berisiko menimbulkan ketidakakuratan karena berisi generalisasi. Dengan slogan tersebut, Golkar secara implisit seolah menyatakan dua hal sekaligus. Pertama, Golkar menyatakan bahwa dirinya merupakan institusi yang layak dan mempunyai legitimasi untuk meyuarakan aspirasi rakyat. Kedua, setiap hal yang disuarakan Golkar seolah-olah merupakan suara rakyat juga. Padahal, sikap yang diambil oleh Golkar tidak selalu diambil berdasarkan perhitungan aspirasi rakyat. Partai pada kenyataannya tidak memiliki energi dan mekanisme tertentu untuk selalu meminta pertimbangan konstituen ketika setiap kali mereka mengambil keputusan. Malah, seringkali keputusan politik partai beringin tersebut justru diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan elit.
Ketika menggunakan strategi bahasa dalam wacana politik, generalisasi dan simplifikasi tidak hanya bisa terjadi secara khusus pada politisi dan partai tertentu saja. Setiap aktor politik dan partai yang diusungnya selalu memiliki kemungkinan untuk melakukan logical fallacy dalam bentuk orasi politis dengan pola pikir yang general (menyamaratakan kesimpulan) dan simplifikatif (terlalu menyederhanakan).
Selayaknya lingkaran ilmu pengetahuan yang memperlihatkan siklus mata rantai filosofisnya, masih banyak analisis bahasa yang bisa digunakan untuk membedah strategi bahasa yang digunakan para aktor politik ketika melemparkan wacana politis tertentu. Ketepatan analisis bahasa seperti yang diuraikan di atas akan selalu menjadi kebenaran sementara (hypo-knowledge) yang pada suatu saat akan terfalsifikasi dalam bentuk ragam rupa analisis yang sesuai dengan parameter dan indikator yang mengiringinya, baik itu analisis yang bersifat aksidensial, lokalitas, kontekstualitas, ataupun karena memang sudah lemahnya jari-jari kebenaran analisis bahasa politik diatas dalam mencengkram suatu permasalahan.
Terkait berbagai gestur bahasa politik tersebut di atas paling tidak bisa dijadikan rujukan untuk melihat aspek-aspek tertentu tentang pesan yang disampaikan politisi. Penukilan beberapa aktor politik dan partainya di atas hanya dilakukan demi kepentingan studi kasus agar penyampaian studi tentang politik bahasa dan penggunaan strategi bahasa dalam wacana politis memiliki relevansi yang bisa dipelajari dan dijadikan refleksi di masa mendatang. Dengan demikian, penulis dalam hal ini tidak memiliki kepentingan politik dengan aktor dan partai politik manapun. Tetapi dari gestur dan bahasa kita dapat memahami sejauhmana politisi itu bertanggungjawab atas ucapannya.
Dan dengan mempertimbangkan beberapa peristiwa politik di masa lalu, seperti kontekstasi pilpres 2014 dan 2019 antara Jokowi versus Prabowo Subianto yang ber-rivalitas. Namun pada akhirnya berkompromi secara politik di Pilpres 2024 yang pada akhirnya mengubur semua fenomena rivalitas itu. Pada akhirnya bahasa politik muncul dengan narasi baru “saling menjaga” dan itu dibuktikan pada perayaan HUT ke 17 Gerindra di Hambalang, pidato Presiden Prabowo dengan berapi-api dengan teriakan hidup Jokowi di tengah demo “Adili Jokowi” di mana-mana. Dan sementara pada ruang yang sama dalam sambutan Jokowi (mantan presiden ke 7 RI) mengungkapkan dengan gamblang dengan kalimat “saat ini pak Prabowo adalah presiden terkuat, dan sampai sekarang tidak ada yang berani mengkritik”
Dari dua frase tersebut, justru seperti “memaksa semut untuk mengerumuni garam” yang pada akhirnya memunculkan sarkasme diberbagai jejaring media sosial dan kemarahan publik dalam hal ini kelompok mahasiswa yang menjejali jalanan sebagai ruang politiknya. Gaya bahasa dari dua pemimpin nasional tersebut ibarat beralas pantun, saling memuji, saling melindungi---sehingga publik menilai kalau rezim saat adalah pelanjut dari rezim sebelumnya yang bergerak tanpa perubahan.
Dan yang paling menohok adalah “pengkritik” justru dibalas dengan kalimat “ndasmu” yang merupakan narasi cacian. Atau benar kata Charles De Gaulle “bahwa politisi itu mengucapkan sesuatu yang ia tidak pahami, tetapi ia heran kalau rakyat mempercayainya” Tetapi paling tidak seorang pemimpin dituntut untuk mengucapkan kata-kata yang baik, bijak, elegan agar pesan yang disampaikannya tidak memberikan rasa takut, membuat kegaduhan, tidak menyakiti orang lain. Karena bahasa adalah cermin dari pengucapnya.
Dan kalimat indah dari George Orwell “Politik dirancang untuk berbohong agar terdengar jujur, bahkan pembunuhan pun didesain agar terlihat terhormat”
“Tinggikan martabat kata-kata, agar tidak jatuhdan melukai”
Oleh: Saifuddin
Direktur Eksekutif LKiS
Dosen, Penulis Buku, Kritikus Sosial Politik, dan penggiat Demokrasi
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan MURIANETWORK.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi MURIANETWORK.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.





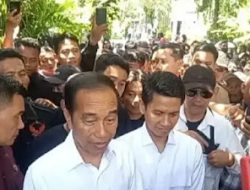





Artikel Terkait
Heboh Link Video Elga Puruk Cahu Berdurasi 5 Menit 44 Detik Viral di Media Sosial
Penegakan Hukum Era Prabowo Maju, Tapi Mandek di Oligarki dan Petinggi Koalisi
Amran Sulaiman: Ada Pengamat dari Kampus Ternama bakal Dipenjara
Akhirnya Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli dari SD sampai Kuliah UGM, Tapi Kok...